Karya : Saepul Nurdin
Jakarta, 02 Desember 2010
Kepada sahabatku,
Saepul Nurdin
Kawan, sebelumnya aku mohon maaf karena baru kali ini aku menyempatkan diri menulis surat untukmu. Kau tahu? Akhir-ahir ini aku terlalu disibukkan oleh siksa kubur yang harus kujalani. Untuk itu mohon maklumi aku.
Bagaimana kabarmu hari ini, kawan? Lama kita tak bersua. Kudengar kau kini sudah menjadi seorang penulis. Aku bangga padamu. Tak kusangka. Dulu, kau hanya seorang pecundang yang selalu keok dalam menghadapi permainan caturku. Dulu, kau juga seorang banci yang tak pernah berani mencolek tahi lalat Pak Situmorang, guru Kimia kita saat SMA yang terkenal bertangan dingin.
Tapi inilah kau sekarang. Kini bagiku, kau jauh lebih canggih daripada teori mesin waktu yang dikemukakan Jhon Titor.
Sebaliknya, jangan pernah kau tayakan bagaimana kabarku sekarang. Kau tahu? Aku menderita di sini. Dan penderitaanku tak akan pernah bisa terjelaskan oleh bahasa dan kalimat manusia. Ya, sekalipun kau penulis hebat. Kata-katamu tak akan pernah mampu mendeskripsikan sakitnya siksaan yang harus kuterima.
Ah, sudahlah! Tak usah kujelaskan penderitaan yang kualami akibat dosa yang sempat kujalani semasa hidup itu, karena memang aku tak mampu menjelaskannya. Dan mungkin tak akan pernah mampu.
Saepul sahabatku, kau pasti heran kenapa tiba-tiba aku menulis surat ini untukmu. Jawabannya sederhana. Aku hanya ingin menyumbangkan ide untukmu. Sebagai seorang penulis, aku tahu kau butuh ide cerita untuk karya-karyamu. Maka kini aku sempatkan diri menulis surat ini untukmu dengan harapan apa yang akan aku ceritakan dalam surat ini bias kau jadikan bahan cerita dalam cerpen atau novelmu kelak.
Sahabatku, kau masih ingat gadis misterius yang pernah kuceritakan padamu enam tahun yang lalu? Kemarin lusa, aku bertemu dengannya. Ia mengenakan kerudung merah yang hanya menutupi sebagian kepalanya ketika aku menemuinya. Dia juga terlihat sangat kurus dan bahkan aku mengira beberapa bagian tulangnya sudah bolong dimakan rayap.
Pada awalnya aku tidak mengenalinya, sampai akhirnya dia menyapaku dengan sapaan terindah yang pernah dilontarkan seorang gadis. Ia menyapa dan menyebut namaku dengan lembut. Lalu tersenyum dengan senyuman khas seorang hantu
(to be continue…)
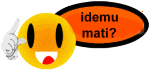
Copy-Paste kode di bawah, untuk pasang banner ini....
untuk pilihan Banner lain, silakan Temans Klik di sini
Karya Ipung
- Banner n Blog Info (2)
- Based on True Story (2)
- buku (4)
- Cerpen (10)
- Essay (1)
- Fiksi Mini (1)
- FlashFiction (4)
- Lagu (1)
- Monolog (1)
- Motivasi (2)
- News n Info (2)
- novel (2)
- Photo (1)
- Puisi (5)
Rekomendasi Karya(4Download)
Gimana blog ini menurut kamu?
Minggu, Desember 05, 2010
Surat dari Hantu Sahabatku
Diposting oleh
Ipung Arraffa
di
12.23
1 komentar
![]()
Cinta dan Tuhan yang Terlupakan
(Juara Favorit Lomba Menulis Cerpen Remaja [LMCR] Lip Ice - Selsun Awarad 2010 - Tingkat Nasional)
Ada saat dimana aku merasa semua orang yang dulu katanya sangat aku banggakan, kini hanya sebatas kumpulan alien asing yang sama sekali tak ku kenal. Bahkan orang-orang yang menurut mereka sangat mencintai akupun, kini tak lebih dari sekedar seorang figuran dalam hidupku yang mempunyai probabilitas nihil untuk meraih piala Oscar.
Sanjungan-sanjungan mereka mengenai kehebatanku dalam menulis puisi, essay, cerpen, roman dan novel, kini hanya menjadi sebuah sejarah palsu untukku. Sejarah yang seakan tak pernah terjadi sama sekali.
Lalu janji-janji yang katanya pernah ku umbar, kini hanya sebatas dongeng murahan pengantar mimpi para cecunguk.
Bukan hanya itu, bahkan nama Tuhan yang dulu susah payah dikenalkan seorang wanita tua—yang katanya ibuku, kini tak ku kenal lagi.
“Tuhan apa? Apa itu Tuhan? Siapa?” Tanyaku bodoh. Maka sejurus kemudian, wanita tua itu menampar ganas pipiku sebagai jawaban atas pertanyaan bejatku.
Mengerikan. Sangat mengerikan memang ketika aku harus kembali ke titik nol. Titik yang merampas semua database dalam otakku.
“Kecelakaan sialan itu merebutmu dariku La...”. Teriak seorang gadis cantik yang duduk lemah di atas kursi kayu tepat di samping kiriku. Air mata gadis itu mulai menerobos, mendobrak kebungkaman kelopak mata indahnya. Bibirnya bergetar puluhan scala richter, mengguncangkan kebekuan jutaan partikel yang menggentayangi wajah manisnya. Tubuhnya seperti tak bertulang. Sangat lemah. Melebihi lemahnya imanku yang sempat menguap tak bersisa.
“Kenapa La? Kenapa kamu diam saja? Kenapa?”
Mataku tak mampu memandangnya sedetikpun. Bukan hanya karena tak sanggup melihat kesedihan yang membungkus wajahnya, tapi juga karena memang aku tidak mempunyai jawaban untuk menjawab pertanyaan gadis itu.
Bahkan aku mungkin tidak menyimak pertanyaannya itu, karena sejak tadi aku sibuk menggaris bawahi sepotong kata: "La" yang dilontarkan gadis itu. Dia memanggilku "La", karena aku tahu namaku Bala. Atau lebih tepatnya: karena aku baru tahu beberapa hari lalu bahwa namaku Bala. Ya, aku sempat lupa siapa namaku. Hingga wanita tua yang akhirnya kusebut Ibu itu mengenalkan aku pada diriku sendiri. Mengenalkan bahwa namaku Bala. Arbala Abdurrahman.
"Atau jangan-jangan kamu masih belum mengenalku La?" Gadis itu kembali bertanya kecewa. Sementara aku masih diam terbaring kaku di atas ranjang besi yang sudah berbau karat. Ranjang itu berdecit setiap kali gadis di sampingku menumpukan tangannya pada sisi ranjang saat memperbaiki posisi duduknya di atas kursi doyong.
“Aku Sissy, La. Tunanganmu”. Tangan gadis itu meremas jemari tanganku yang kaku. “Entah sudah berapa kali aku mengenalkan diri padamu. Berkali-kali aku berusaha membuatmu kembali mengenalku dengan harapan bisa membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Dan aku sudah kehilangan akal untuk membuatmu mengenalku apalagi membuatmu kembali jatuh cinta padaku. Semua cara sudah aku coba untuk membuatmu mengenalku. Tapi usahaku rupanya sia-sia belaka. Bahkan setiap kali aku bertanya padamu tentang apa yang bisa membuatmu mengenalku dan jatuh cinta lagi padaku, maka kamu selalu saja diam.
Lalu apalagi yang bisa membuatmu mengenalku kemudian jatuh cinta padaku?
Padahal aku sudah menulis puluhan puisi cinta untukmu yang dulu kamu ajari aku membuatnya, tapi aku lupa bahwa kamu sudah lupa bagaimana caranya membaca. Berkali-kali aku menyanyikan lagu cinta yang dulu kamu sering menghujatku karena suaraku fals tak karuan, tapi sial, aku lupa bahwa bibirmu sudah lupa bagaimana caranya bernyanyi. Sering sekali aku bercerita tentang mimpi-mimpi muluk masa depan yang dulu kamu paksa aku memilikinya, tapi aku lupa bahwa kamu ternyata sudah lupa mimpi-mimpimu sendiri. Bahkan sungguh aku tidak tahu, apakah saat ini kamu mempunyai mimpi atau tidak.
Aku lupa bahwa ternyata kamu lupa semuanya. Semuanya La. Bahwa kamu lupa pidato calon legislatif yang dulu kamu jadikan bahan guyonan. Bahwa kamu lupa karya ilmiahmu yang mensejajarkan antara primbon dan teori kekekalan energi. Bahwa kamu lupa kebiasaan burukmu yang selalu saja lupa hari ulang tahunmu sendiri. Bahwa kamu lupa jampi-jampi ajaib yang pernah kamu ajarkan padaku agar sakit gigiku sembuh. Bahwa kamu lupa dongeng-dongeng lucu yang sering kamu ceritakan setiap kali aku menangis. Kamu lupa semuanya, La...”. Gadis itu mulai memaksakan senyumnya. Senyum yang selepas apapun ia hadirkan namun ternyata tak mampu menanggalkan rasa sedih dari wajahnya yang terlalu manis untuk sebuah kesedihan.
“Kamu lupa bagaimana caranya kamu mencium bibirku yang sebenarnya tidak pernah kamu lakukan. Kamu lupa bagaimana caranya menghapus air mataku yang sebenarnya tak pernah kamu tunjukkan. Kamu juga lupa bagaimana caranya menyematkan hiasan di rambutku yang ternyata tak pernah kamu sematkan. Kamu lupa semuanya”.
Gadis itu tertunduk lemas. Ia menjatuhkan air matanya yang hangat di atas punggung tanganku yang tak mampu ia lepaskan dari genggamannya.
“Kecelakaan itu membuatmu melupakan semuanya La. Melupakan semua yang justru tak pernah bisa aku lupakan.
Tahukah kamu La? Setiap pagi, sebelum kamu terbangun dari tidur, aku selipkan sepucuk surat cinta di bawah bantal bolongmu dengan harapan kamu membacanya penuh iba, hingga akhirnya kamu kembali mencintaiku seperti dulu. Karena kamu tahu bahwa surat-surat itu berisikan tulisan yang sama, yaitu cerita tentang saat pertama kali kamu jatuh cinta padaku. Sebuah cerita yang menjabarkan kisah tentang segala sesuatu yang dulu membuatmu jatuh cinta padaku. Kisah yang tak pernah bisa aku lupakan, namun justru dengan kejam kamu lupakan.
Surat itu mengisahkan bagaimana pertemuan pertama kita yang tak pernah kita ketahui kapan waktunya. Pertemuan pertama yang tak seperti kisah dalam sinetron yang meninggalkan kesan begitu mendalam, karena pertemuan pertama kita hanyalah pertemuan dua orang anak kecil yang mengawali permainan petak umpet di halaman sekolah dasar. Dan tak seperti kisah-kisah dalam roman yang menjadikan tokohnya jatuh cinta pada pandangan pertama, maka cinta kita tumbuh apa adanya. Cinta yang tanpa kita sadari terjadi begitu saja. Cinta sederhana yang ditumbuhkan oleh waktu dan frekuensi bertemu. Bahkan jujur, aku tak menayadari datangnya cinta itu. Butuh waktu bertahun-tahun untukku menyimpulkan bahwa ternyata aku jatuh cinta padamu. Aku hanya menyadari bahwa ada rasa bahagia setiap kali aku mendengar suara motor bututmu yang memekakkan telinga. Maka hal itu kujadikan dasar bahwa ternyata aku jatuh cinta padamu. Ya, rasa bahagia setiap kali aku mendengar suara motor bututmu kujadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa aku jatuh cinta padamu.
Lalu surat itu pun mengisahkan bagaimana pertama kali kamu menyimpulkan bahwa kamu mencintai aku. Kamu yakin bahwa kamu mencintai aku setelah kamu diracuni ilmu primbon oleh tetanggamu yang berprofesi sebagai dukun sesat. Tak seperti dalam dongeng yang mengisahkan ungkapan cinta seorang kekasih untuk kekasihnya dalam suasana romantis, maka kamu mengungkapkan perasaanmu dalam suasana penuh mistis. Kamu menceritakan mimpimu yang dalam buku primbon berarti kamu telah menemukan pasangan hidupmu. Maka atas dasar ilmu primbonlah kamu yakin bahwa kamu mencintai aku”. Gadis itu kembali memaksakan senyumnya. Senyum sinis yang berusaha menyembunyikan kesedihannya.
“Kamu tahu hari ini adalah hari ketiga puluh sejak kecelakaan itu merenggut ingatanmu dariku, maka tiga puluh pucuk surat cinta itu pun tertumpuk di bawah bantal horormu yang dipenuhi gigitan tikus. Aku tidak tahu apakah surat-surat itu sudah kamu baca atau belum, yang aku tahu, bahwa setiap pagi aku selalu berusaha membuatmu jatuh cinta lagi padaku”. Air mata gadis itu kini membanjiri punggung tanganku. Setiap isak tangisnya adalah tusukan belati beracun yang sewaktu-waktu bisa membunuhku.
“Lalu apakah sebuah kesalahan jika aku mengemis suatu kenyataan dimana kamu mencintai aku lagi? Jawab La! Jawab! Jangan diam saja! Aku mohon! Jawab! Jawab La! Jawab…” Tangisnya semakin menjadi-jadi. Maka isakkannya yang serupa belati beracun itu tak henti mencabik setiap lapisan organ dalam hatiku. Ia merobek sisi rasionalku, lalu meruntuhkan hukum-hukum fisika yang selama ini menjamuri otakku.
Gadis cengeng itu menciumi punggung tanganku yang sudah basah sambil tak henti memohon seperti pengemis yang mengobral penderitaan. Air matanya tak terbendung hingga akhirnya dengan payah ia mengangkat kepalanya yang sejak tadi tertunduk lemas. Lagi-lagi ia memaksakan senyumnya yang hambar.
“Hmmmm... Aku lupa bahwa kamu sudah melupakan semuanya. Dan kamu lupa bagaimana caranya menjawab pertanyaan. Maka kamu hanya diam. Ya, hanya diam yang ternyata tidak kamu lupakan. Kamu masih hapal benar bagaimana caranya diam. Sialnya aku lupa bahwa kamu hanya bisa diam. Maafkan aku La, aku hanya ingin kamu mencintai aku. Lagi. Seperti dulu. Sebelum kamu melupakan aku. Itu saja!”.
Kalimatnya meruntuhkan setiap keangkuhan dan kesombonganku. Dengan sangat berat, pandanganku yang sejak awal terpaku pada atap rumahku yang bobrok, kini kualihkan ke arah wajah gadis itu yang meskipun melepaskan senyuman namun kesedihan masih saja membungkus wajahnya.
“Maaf La. Lagi-lagi aku lupa bahwa mencintai seseorang yang tidak kamu kenal sama sekali adalah sebuah kesulitan yang teramat sangat. Dan mengenalkan diriku padamu adalah sebuah kesulitan teramat sangat yang lain. Kesulitan yang berulang kali memaksa air mataku membanjiri punggung tanganmu. Apakah tak ada sepatah kata pun yang mengabarkan hal itu padamu? Maafkan aku La..”
Gadis itu menangis lagi. Dan aku diam lagi. Menutup mataku lagi.
Gelap mulai menghapus semua titik cahaya di setiap sudut mataku. Ia pun merobek garis-garis sinar di setiap tepian imajenasiku. Bahkan gelap tengah menyumpal kedua lubang telingaku, sehingga isak gadis itu pun raib di ujung pendengaranku. Semuanya lenyap dan aku tak ingat lagi. Semuanya sirna begitu saja. Hilang.
Ah, sial. Aku tak ingat lagi.
***
Gadis itu sudah tak ada di sampingku lagi ketika kubuka mata. Tak kudengar lagi isak tangisnya namun air matanya masih tergenang di atas punggung tanganku. Air mata itu seolah melelehkan kulit tanganku dan menjilati belulangku dengan rakus.
"Almarhum ayahmu, Le!" Seorang wanita tua yang sudah bungkuk dan payah mengagetkanku dengan suaranya yang horor. Entah sejak kapan ia berada di sana. Di salah satu sudut kamar.
"Almarhum ayahmu pasti akan mengurungmu di kandang kambing lagi kalau dia tahu kamu melupakan Tuhanmu, Le!" Lanjut wanita tua yang kusebut Ibu itu sambil membereskan obat-obatan dan sisa sarapanku di meja kayu yang tepiannya sudah berlumut.
"Susah payah kami mengenalkan Tuhan padamu Le, tapi kecelakaan itu mengambil nama Tuhan dalam hati dan otakmu hanya dalam waktu beberapa detik saja".
Ibu tua itu mulai berjalan tertatih menghampiriku sambil mengeluarkan sejumput daun sirih dari sela-sela kain samping yang meliliti perut keriputnya, kemudian dengan ganas mengunyah daun sirih itu seperti kerbau melahap rumput.
Tak lama ia duduk di samping kiriku sehingga ranjang reyotku berdecit kesakitan menahan berat badan wanita tua bernama Ibu itu.
"Coba kamu ingat-ingat lagi Le nama Tuhanmu!" Ibu mulai memohon sambil memperbaiki letak selimut yang menutupi tubuhku. Selimut tua yang sepanjang sisinya sudah tercabik-cabik.
"Emak khawatir, jika nanti malaikat menanyaimu tentang siapa Tuhanmu, lantas kamu diam saja seperti ini. Emak malu sama malaikat, Le. Terlebih sama Tuhan. Emak malu”.
Aku memandangi wajahnya yang penuh harap. Wajah yang dipenuhi keriput namun tak pernah terlihat lelah. Wajah wanita tua itu seperti penggambaran cinta yang sesuangguhnya.
“Kamu juga pasti tahu Le kisah tentang suatu kaum yang melupakan Tuhannya, kemudian kaum itu dibinasakan sejadi-jadinya. Emak tidak mau hal itu terjadi padamu, Le. Terjadi pada kita! Makanya Emak mohon, ingat nama Tuhanmu, Le. Emak mohon!”.
Ia memegang tanganku, kemudian meremasnya. Sangat erat, sehingga aku dapat merasakan aliran darah mengalir deras dalam tubuh peotnya. Matanya yang sayu menusuk retina mataku dengan jutaan harapan. Giginya yang kuning dan panjang seperti bambu runcing para pejuang mulai bergemulutuk hebat.
Aku lihat bibirnya mulai menuntunku mengingat nama Tuhan.
"Katakan: Allah!" Bisiknya pasti. Kalimatnya membuat badanku bergetar dahsat. Tremor mengguncang ranjang bututku. Keringatku menyembur dari berbagai celah pori-pori.
"Allah..." Ibu terus menuntunku dengan harapan bibir dan lidahku segera mengucapkan nama Tuhan.
Tiba-tiba badanku panas. Tubuhku menggigil. Nafasku seperti tersangkut dalam kerongkongan. Lalulintas darahku kacau dan jantungku lelah. Nadiku mematung sedangkan otak membeku, tak mampu lagi berpikir. Apakah ini waktunya aku dibinasakan? Pikirku ngawur. Namun sebelum pertanyaan itu terjwab, gelap kembali mencengkeram mataku. Lalu dengan ganas menutupi lubang telingaku. Dan aku tidak ingat lagi. Aku kembali melupakan semuanya. Semuanya tanpa sisa.
"Bodoh!" kataku dalam hati.
Jakarta, 8 Februari 2009
Diposting oleh
Ipung Arraffa
di
12.06
0
komentar
![]()
Label: Cerpen
